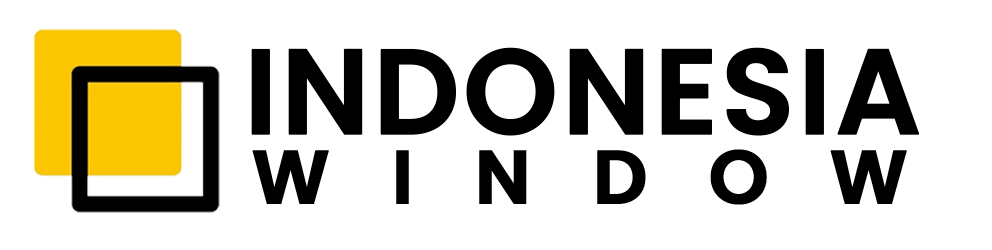Riset BRIN ungkap emisi karbon lamun Indonesia, Jawa dan Sumatra tertinggi

Ilustrasi padang lamun. (Benjamin L. Jones on Unsplash)
Faktor emisi karbon lamun di Indonesia berada pada kisaran 0,53 hingga 3,25 ton karbon per hektare per tahun. Nilai tertinggi ditemukan di wilayah Jawa dan sebagian Sumatra, sementara wilayah seperti Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan Maluku menunjukkan nilai yang lebih rendah.
Jakarta (Indonesia Window) — Ekosistem lamun selama ini dikenal sebagai penyerap karbon alami di wilayah pesisir. Namun, riset terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap sisi lain yang tak kalah penting, yakni lamun juga bisa menjadi sumber emisi karbon ketika rusak. Menariknya, besaran emisi ini tidak sama di seluruh Indonesia.
Hasil riset baru-baru ini menunjukkan bahwa wilayah Jawa dan sebagian Sumatra memiliki faktor emisi karbon lamun tertinggi dibandingkan kawasan pesisir lainnya di Tanah Air. Artinya, kerusakan padang lamun di wilayah barat Indonesia berpotensi melepaskan karbon ke atmosfer dalam jumlah lebih besar dibandingkan wilayah timur.
Penelitian ini dilakukan oleh Peneliti Pusat Riset Oseanologi BRIN, A’an Johan Wahyudi, melalui kajian ilmiah yang secara khusus menghitung emisi karbon akibat degradasi ekosistem lamun.
Lamun menyerap dan melepas karbon
Selama ini, pembahasan tentang karbon biru lebih banyak menyoroti kemampuan ekosistem pesisir—termasuk lamun—dalam menyerap dan menyimpan karbon. Padahal, menurut A’an, aspek emisi akibat kerusakan ekosistem justru sering luput dari perhatian.
“Kalau kita bicara karbon biru, fokusnya selalu pada penyerapan. Padahal, dalam carbon accounting, yang dihitung bukan hanya yang diserap, tetapi juga yang dilepaskan ke atmosfer,” ujar A’an dalam wawancara khusus, Rabu (14/1).
Dia menjelaskan, lamun yang sehat mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam biomassa dan sedimen. Namun, kondisi tersebut berubah ketika lamun mengalami gangguan akibat aktivitas manusia di wilayah pesisir.
Reklamasi hingga sedimentasi jadi pemicu emisi
Aktivitas seperti reklamasi pantai, pengerukan, hingga peningkatan sedimentasi akibat erosi daratan dapat menghambat pertumbuhan lamun dan memicu degradasi ekosistem.
“Sederhananya, ketika lamun sehat, karbon diserap dan disimpan. Tapi ketika rusak—misalnya karena reklamasi—daun dan akar lamun akan membusuk. Proses pembusukan inilah yang melepaskan karbon dioksida ke atmosfer,” jelasnya.
Lamun memang memiliki kemampuan menyaring sedimen, namun kemampuan tersebut tidak tak terbatas. Jika sedimen yang masuk terlalu banyak, keseimbangan ekosistem tetap akan terganggu.
Dalam riset ini, A’an memperkenalkan konsep faktor emisi karbon lamun, yaitu angka yang menunjukkan seberapa besar karbon dilepaskan ke atmosfer per hektare ekosistem lamun per tahun akibat degradasi.
Selama ini, Indonesia masih menggunakan faktor emisi global (Tier-1 IPCC) untuk menghitung emisi karbon lamun. Menurut A’an, pendekatan ini kurang mencerminkan kondisi Indonesia yang sangat beragam.
“Kondisi lamun Indonesia berbeda-beda, baik dari tekanan aktivitas manusia, dinamika pesisir, maupun stok karbonnya. Angka rata-rata global tidak bisa mewakili semuanya,” ujarnya.
Wilayah Jawa dan sebagian Sumatra, misalnya, memiliki tekanan antropogenik jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan timur Indonesia yang relatif masih alami.
Untuk mengatasi keterbatasan data jangka panjang, A’an menggunakan metode chronosequence modeling, yakni membandingkan kondisi padang lamun yang masih baik dengan yang telah terdegradasi.
“Hampir tidak ada data kondisi lamun 10–20 tahun lalu. Maka, wilayah dengan lamun yang masih bagus seperti Nusa Tenggara Timur dijadikan referensi kondisi masa lalu,” jelasnya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor emisi karbon lamun di Indonesia berada pada kisaran 0,53 hingga 3,25 ton karbon per hektare per tahun. Nilai tertinggi ditemukan di wilayah Jawa dan sebagian Sumatra, sementara wilayah seperti Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan Maluku menunjukkan nilai yang lebih rendah.
“Wilayah padat penduduk dengan tekanan pesisir tinggi memiliki potensi emisi yang lebih besar,” kata A’an.
Temuan ini menegaskan bahwa lokasi kerusakan lamun sangat menentukan besarnya emisi karbon, meski luas area yang rusak sama.
Melalui riset ini, Indonesia didorong untuk mulai beralih dari pendekatan global Tier-1 ke Tier-2, yakni menggunakan faktor emisi yang lebih spesifik dan sesuai kondisi nasional.
Meski begitu, A’an menekankan bahwa angka faktor emisi yang dihasilkan saat ini masih bersifat awal karena baru menghitung karbon dari biomassa lamun.
“Padahal, cadangan karbon terbesar justru tersimpan di sedimennya,” ujarnya.
Ke depan, penggabungan data biomassa dan sedimen dinilai penting agar perhitungan emisi karbon lamun semakin akurat dan dapat mendukung pelaporan penurunan emisi nasional, termasuk dalam kerangka Nationally Determined Contribution (NDC).
Untuk menjaga ekosistem lamun tetap lestari, A’an menekankan pentingnya regulasi yang kuat, penegakan aturan yang konsisten, serta keterlibatan masyarakat pesisir—mulai dari pengelolaan sampah hingga pembangunan yang lebih ramah lingkungan.
Dia juga menyoroti urgensi penguatan sistem pemantauan laut jangka panjang melalui Indonesia Ocean Observing System (IOOS), yang tidak hanya memantau kondisi fisik laut, tetapi juga aspek biogeokimia dan ekosistem.
Laporan: Redaksi
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Satelit China tangkap gambar suar Matahari yang kuat
Indonesia
•
04 Jan 2024

Studi di China soroti penuaan sumsum tulang belakang
Indonesia
•
04 Nov 2023

Studi di Selandia Baru tunjukkan El Nino perpanjang musim serbuk sari dan risiko alergi
Indonesia
•
18 Sep 2025

Terobosan degradasi protein presisi buka jalan baru pengobatan modern
Indonesia
•
19 Jan 2026
Berita Terbaru

Deforestasi dan perubahan pemanfaatan lahan intensifkan gelombang panas global
Indonesia
•
29 Jan 2026

Batu bergagang berusia 70.000 tahun ditemukan, mitos keterlambatan teknologi Asia Timur terpatahkan
Indonesia
•
29 Jan 2026

Palem nyabah di ujung tanduk, BRIN amankan ‘cetak biru genetik’ untuk selamatkan warisan Bali
Indonesia
•
28 Jan 2026

Hingga akhir 2025, stasiun pemancar 5G di China tembus 4,83 juta unit
Indonesia
•
28 Jan 2026